
Schoolmedia News Jakarta = Di pesisir Pulau Pari yang tergerus abrasi, di bawah bayang-bayang gunungan sampah Bantar Gebang, hingga di koridor Rusunawa Marunda yang berdebu batu bara, krisis iklim bukan lagi sekadar prediksi saintifik.
Bagi masyarakat rentan, ia adalah penindas baru yang memperdalam luka kemiskinan dan ketimpangan struktural. Di tengah respons negara yang masih jauh dari optimal, komunitas-komunitas ini terpaksa merajut sendiri jaring penyelamat demi mempertahankan hidup.
Laporan penelitian terbaru bertajuk "Solusi Krisis Iklim Berbasis Komunitas" yang dirilis oleh Greenpeace Indonesia bersama The SMERU Research Institute pada awal 2026, menyingkap realitas pahit di tiga titik episentrum kerentanan Jakarta dan sekitarnya. Dengan menggunakan pendekatan metode gabungan (mixed-methods), studi ini membedah bagaimana krisis iklim berkelindan dengan masalah ekonomi dan sosial, menciptakan siklus kerentanan yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang radikal.
Trilogi Kerentanan Warga
Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meski secara geografis berbeda, Pulau Pari, Bantar Gebang, dan Rusunawa Marunda diikat oleh "tiga dosa" struktural yang sama. Pertama, degradasi lingkungan yang akut. Di Pulau Pari, kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem mengancam ruang kelola rakyat. Di Bantar Gebang, warga hidup berdampingan dengan risiko ekologis sampah, sementara di Marunda, polusi industri menjadi beban tambahan bagi kesehatan warga.
Kedua, ekonomi rumah tangga yang rapuh. Analisis kemiskinan dalam studi ini menunjukkan bahwa krisis iklim secara simultan menekan pendapatan warga. Biaya hidup meningkat karena warga harus beradaptasi secara mandiri—mulai dari meninggikan lantai rumah hingga biaya pengobatan akibat lingkungan yang tidak sehat.
Ketiga, lemahnya tata kelola dan perlindungan sosial. Penanganan formal oleh negara dianggap belum menyentuh akar persoalan. Kebijakan yang ada sering kali bersifat top-down dan abai terhadap realitas lokal, sehingga warga merasa harus berjuang sendiri dalam menghadapi risiko yang kian mendesak.
Sebagai respons terhadap absennya dukungan sistemik, solusi berbasis komunitas tumbuh secara organik di ketiga wilayah tersebut. Di Pulau Pari, komunitas nelayan dan pelaku wisata lokal memperkuat ketahanan ekologis melalui penanaman mangrove dan advokasi perlindungan wilayah pesisir. Inisiatif ini bukan sekadar upaya konservasi, melainkan strategi bertahan hidup agar mata pencaharian mereka tidak tenggelam ditelan rob.
Di Bantar Gebang, warga mengembangkan mekanisme adaptasi melalui lembaga ekonomi komunitas dan pengelolaan lingkungan lokal. Mereka menciptakan jejaring sosial sebagai jaring pengaman saat krisis kesehatan atau ekonomi melanda akibat dampak lingkungan sampah yang ekstrem.
Sementara itu, di Rusunawa Marunda, warga mengorganisasi diri untuk menghadapi polusi udara dan keterbatasan akses air bersih. Penguatan layanan sosial mandiri dan jejaring informasi menjadi modal utama untuk memitigasi risiko kesehatan yang terus menghantui anak-anak dan lansia di sana.
Ketimpangan dan Batas Kemampuan Warga
Namun, laporan Greenpeace dan SMERU ini memberikan peringatan keras: inisiatif lokal memiliki batas napas. Studi ini menemukan bahwa efektivitas dan keberlanjutan solusi komunitas terganjal oleh minimnya dukungan kelembagaan dan keterbatasan pendanaan.
"Negara tidak bisa terus-menerus membiarkan komunitas menanggung beban adaptasi sendirian. Ada ketimpangan internal dan keterbatasan sumber daya yang membuat solusi organik ini rentan goyah," kutip laporan tersebut. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa tanpa pengakuan hukum dan integrasi ke dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas, upaya warga ini hanya akan menjadi tambal sulam di tengah lubang krisis yang kian membesar.
Ada pula aspek ketimpangan internal di mana kelompok paling miskin di dalam komunitas tersebut justru paling sulit mengakses manfaat dari inisiatif lokal karena keterbatasan modal dan waktu. Hal ini menegaskan bahwa krisis iklim adalah masalah keadilan sosial yang memerlukan pendistribusian ulang sumber daya secara adil.
Menghadapi tahun 2026 yang penuh ketidakpastian iklim, penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan yang mendasar. Adaptasi iklim harus bergeser dari sekadar proyek infrastruktur fisik menuju tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah perlu mendukung inisiatif komunitas dengan memberikan kepastian hukum, akses pendanaan yang mudah, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Integrasi antara kerangka global dengan realitas lokal menjadi kunci agar adaptasi berjalan secara sistemik dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Pada akhirnya, ketangguhan Indonesia menghadapi perubahan iklim tidak hanya diukur dari angka-angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa berdaya warga di garis depan—seperti di Pari, Bantar Gebang, dan Marunda—dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Tanpa keadilan, adaptasi hanyalah bentuk lain dari pengabaian.
Tim Schoolmedia


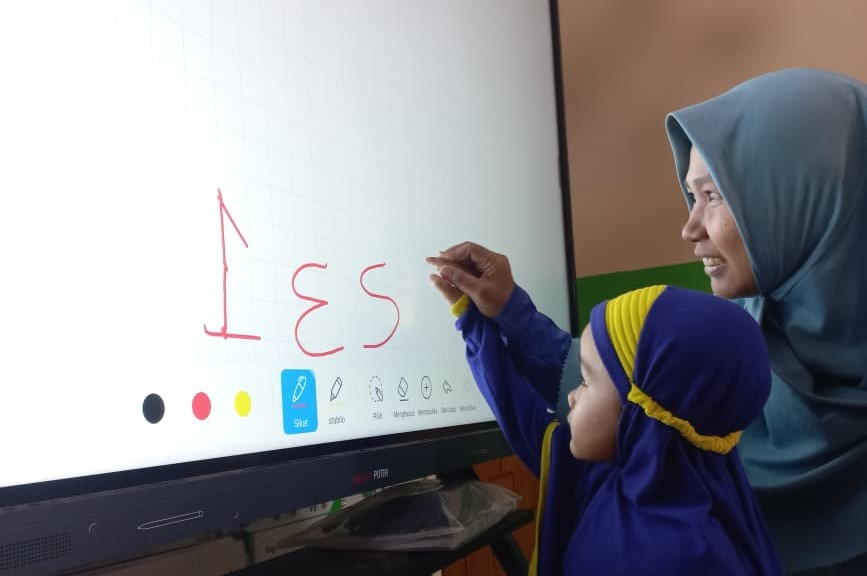



Tinggalkan Komentar