
Schoolmedia News Jakarta — Gelombang penolakan terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian menguat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menilai langkah tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bentuk "penghukuman" terhadap kedaulatan rakyat dan sinyal kuat kemunduran demokrasi di Indonesia.
Isu pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD kembali mencuat di penghujung tahun 2025 dan awal 2026. Sejumlah partai politik di DPR serta pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dinilai memberikan sinyal persetujuan terhadap agenda ini. Namun, bagi para aktivis demokrasi, rencana ini dianggap sebagai upaya sistematis untuk memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elite Jakarta.
Dalam keterangan resmi yang dirilis di Jakarta, Minggu (11/1/2026), Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 20 lembaga—di antaranya Perludem, ICW, PSHK, dan Pusako Universitas Andalas—menyatakan sikap tegas menolak gagasan tersebut. Mereka memandang bahwa mencabut hak pilih rakyat adalah pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan yang dijamin konstitusi.
"Memindahkan hak memilih dari masyarakat kepada DPRD jelas merupakan tindakan yang memundurkan prinsip kedaulatan rakyat. Padahal, hak untuk memilih dan dipilih adalah hak politik yang fundamental," ujar perwakilan koalisi dalam pernyataan tertulisnya.
Ancaman Sentralisasi Kekuasaan
Koalisi menyoroti bahwa di bawah sistem politik yang saat ini sangat terkonsolidasi, pengembalian pilkada ke DPRD akan memperkuat pola sentralisasi kekuasaan. Ada kekhawatiran besar bahwa kepemimpinan lokal nantinya tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan warga daerah, melainkan oleh hasil negosiasi elite partai politik di Jakarta.
Indikasi penarikan kewenangan daerah ke pusat sebenarnya sudah dirasakan sejak berlakunya UU Cipta Kerja. Jika sistem pemilihan juga ditarik ke lembaga perwakilan, maka otonomi daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi nama tanpa substansi.
"Sangat memungkinkan kepala daerah nantinya tidak akan melahirkan kebijakan strategis karena 'tersandera' oleh kepentingan DPRD yang memilihnya. Hubungan check and balances yang seharusnya setara akan berubah menjadi subordinatif," tulis koalisi tersebut.
Kekhawatiran ini didasari pada kondisi faktual saat ini di mana DPRD dinilai belum optimal menjalankan fungsi aspiratifnya. Banyak warga yang justru lebih memilih mengadu lewat media sosial langsung kepada kepala daerah daripada melalui wakilnya di parlemen daerah. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, legitimasi kepala daerah di mata rakyat diprediksi akan merosot tajam.
Politik Uang Diruang Tertutup Makin Luas
Salah satu argumen klasik yang kerap digaungkan pemerintah dan DPR untuk menghapus pilkada langsung adalah biaya politik yang mahal dan tingginya angka politik uang. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil membedah argumen tersebut sebagai sebuah kekeliruan logika.
Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2010-2024, terdapat sedikitnya 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Data ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif daerah tidak steril dari praktik transaksional.
"Masalah politik uang tidak akan hilang hanya dengan memindahkan lokasi pemilihan. Justru, ruang transaksi dalam pilkada oleh DPRD berpeluang lebih besar terjadi di ruang-ruang tertutup yang sulit diakses publik. Ini jauh lebih berbahaya karena pengawasan masyarakat menjadi terbatas," tegas koalisi.
Selain itu, koalisi menekankan bahwa biaya politik yang tinggi sebenarnya disebabkan oleh perilaku peserta pilkada dan partai politik pengusungnya, bukan oleh sistem pemilihan langsung itu sendiri. Menghapuskan hak pilih rakyat dianggap sebagai cara yang salah dalam mendiagnosis masalah korupsi politik.
Dampak lain yang sangat krusial adalah hilangnya peluang bagi calon perseorangan atau independen. Dalam sistem pemilihan oleh DPRD, kompetisi politik lokal hanya akan menjadi panggung bagi partai-partai besar yang memiliki kursi di parlemen.
Dominasi partai politik akan menutup ruang bagi pemimpin alternatif yang tidak terafiliasi dengan partai. Lebih jauh, koalisi mengkhawatirkan adanya skenario di mana Presiden bisa menggerakkan elite partai di pusat untuk menentukan siapa yang harus duduk di kursi kepala daerah, sehingga kontrol eksekutif pusat atas daerah menjadi absolut.
"Apa sesungguhnya tujuan agenda perubahan sistem ini? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Rakyat atau elite?"
Empat Tuntutan Sipil
Merespons situasi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menyampaikan empat sikap resmi:
Menolak keras segala bentuk gagasan untuk mengganti pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.
Mendesak partai politik dan penyelenggara negara untuk fokus mengkaji penguatan kualitas pilkada langsung, bukan menghapusnya.
Menuntut pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) untuk taat pada prinsip demokrasi dan amanat perubahan UUD 1945.
Mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan media untuk mengawal hak politik warga agar tidak dirampas oleh kepentingan jangka pendek elite.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak DPR maupun Istana terkait kritik tajam yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil tersebut. Namun, isu ini diperkirakan akan menjadi sumbu panas perdebatan politik sepanjang tahun 2026, mengingat posisi pilkada sebagai pilar penting demokrasi di tingkat lokal.
Tim Schoolmedia





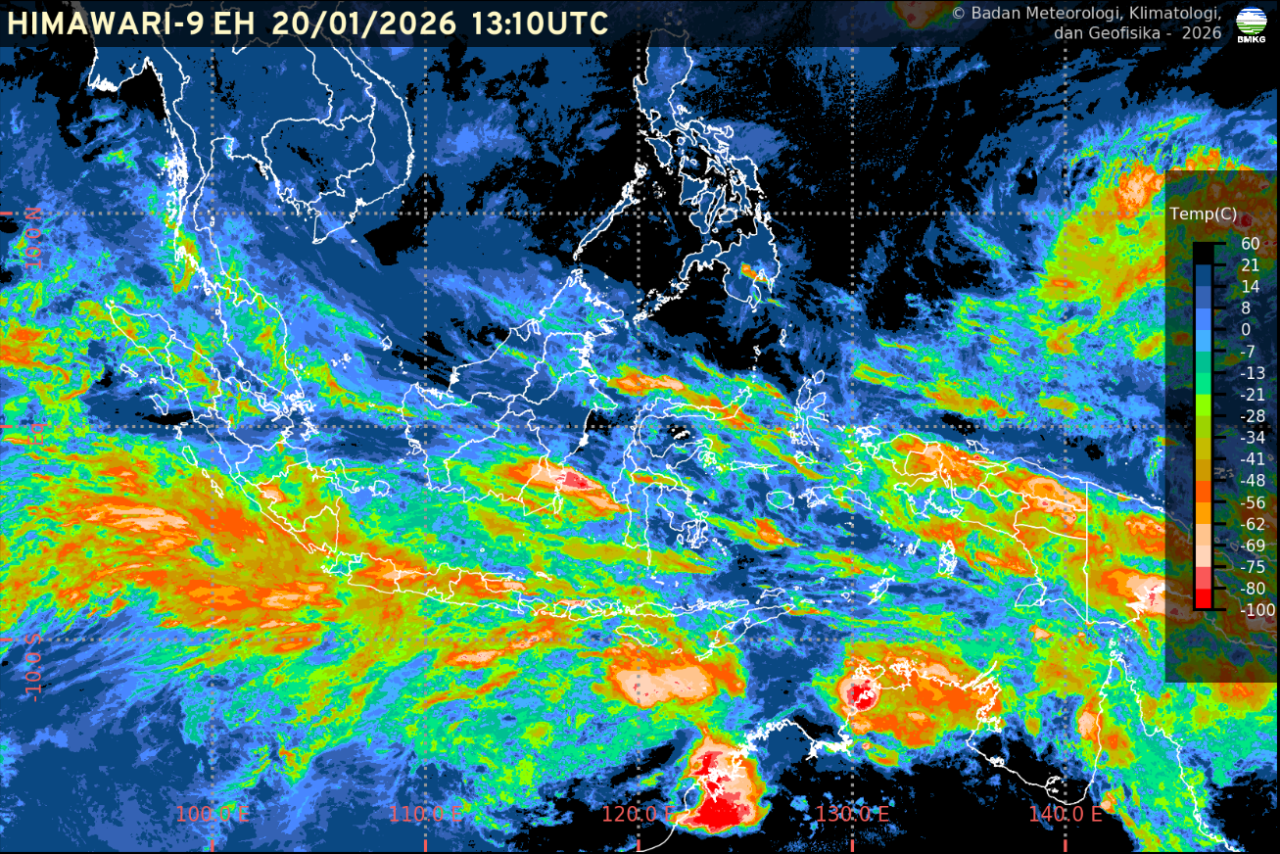

Tinggalkan Komentar