
Schoolmedia News Jakarta = Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dirancang sebagai intervensi sosial untuk menjawab masalah paling mendasar dalam pendidikan: anak yang lapar sulit belajar. Negara hadir melalui makanan, bukan melalui seleksi. Namun arah kebijakan belakangan ini memunculkan kegelisahan baru, ketika hasil program gizi mulai dihubungkan dengan pengukuran kecerdasan—bahkan diwacanakan melalui tes IQ terhadap anak-anak penerima MBG.
Di titik inilah perdebatan muncul. Apakah negara sedang memastikan efektivitas program, atau justru tergelincir pada logika yang menyederhanakan persoalan pendidikan menjadi sekadar skor kognitif?
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Penguatan Karakter merilis hasil evaluasi Program MBG yang terintegrasi dalam kerangka 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH). Survei baseline (Mei–Juni) dan endline (November–Desember) yang melibatkan 11.380 sekolah pelaksana MBG dan 4.045 sekolah non-pelaksana menunjukkan hasil yang konsisten: MBG menurunkan gangguan konsentrasi akibat rasa lapar dan meningkatkan kesiapan belajar murid.
Keluhan lapar yang sebelumnya menjadi distraksi utama dalam proses pembelajaran mengalami penurunan 2,36 poin persentase lebih tajam di sekolah pelaksana MBG dibandingkan sekolah dengan kondisi awal setara yang belum menerima program. Temuan ini mempertegas bahwa intervensi gizi bekerja pada level paling fundamental: memastikan anak hadir di kelas dengan tubuh yang siap belajar.
Gangguan Konsentrasi Akibat Lapar Teratasi
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa dampak ini bersifat strategis. Menurutnya, ketika gangguan konsentrasi akibat rasa lapar teratasi, murid memiliki kesiapan fisik dan kognitif yang lebih baik untuk menyerap ilmu pengetahuan serta membangun karakter unggul.
Data juga menunjukkan dampak signifikan di wilayah Indonesia Timur. Di Papua, Maluku, dan NTT, persentase murid yang terganggu konsentrasinya akibat lapar turun dari 59,2 persen menjadi 38,3 persen. Dibandingkan sekolah non-MBG dengan kondisi awal setara, sekolah pelaksana mencatatkan keunggulan 15,1 persen poin. Bagi banyak pengamat, inilah esensi keadilan sosial: menghapus hambatan struktural agar anak-anak dari wilayah tertinggal memiliki peluang belajar yang setara.
Namun persoalan muncul ketika keberhasilan ini mulai ditarik lebih jauh—dikaitkan dengan pengukuran kecerdasan anak melalui tes IQ. Sejumlah psikolog pendidikan menilai pendekatan tersebut problematik, baik secara metodologis maupun etik.
Psikolog anak dan keluarga menegaskan bahwa tes IQ bukan alat netral, apalagi jika diterapkan pada anak-anak dari latar sosial ekonomi rentan. Tes ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, stimulasi, bahasa, dan pengalaman belajar sebelumnya. Anak yang bertahun-tahun hidup dalam kekurangan gizi dan stimulasi tidak bisa diharapkan “melonjak†secara instan hanya karena beberapa bulan intervensi makan bergizi.
“Yang diukur tes IQ bukan semata potensi, tetapi juga jejak ketimpangan,†ujar seorang psikolog pendidikan. Ketika hasil tes itu kemudian digunakan untuk mengevaluasi program, risiko stigmatisasi menjadi nyata: anak miskin kembali disalahkan karena angka yang tidak naik signifikan.
Salah Kaprah Memahami Tujuan MBG
Pakar kebijakan pendidikan menilai pengaitan MBG dengan tes IQ mencerminkan kekeliruan dalam memahami tujuan program. MBG bukan program akselerasi kecerdasan, melainkan jaring pengaman sosial agar proses belajar bisa berlangsung secara manusiawi.
Menurut mereka, indikator keberhasilan MBG seharusnya berfokus pada kehadiran siswa, konsentrasi belajar, kesehatan dasar, dan iklim kelas yang lebih kondusif—bukan pada lonjakan skor kognitif jangka pendek. Mengharapkan peningkatan IQ sebagai tolok ukur utama justru mengaburkan fungsi utama negara dalam menjamin hak dasar anak.
“Kalau logikanya seperti itu, negara seolah berkata: kami beri makan, sekarang buktikan kamu lebih pintar,†kata seorang pengamat pendidikan. Relasi ini dinilai tidak setara dan berpotensi melanggengkan cara pandang elitis dalam kebijakan publik.
Kritik juga datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada hak anak. Mereka mengingatkan bahwa tes IQ terhadap penerima MBG berisiko menciptakan labelisasi baru—anak “cerdas†dan “tidak cerdasâ€â€”yang dilekatkan sejak usia dini, terutama pada kelompok rentan.
Dalam konteks sosial Indonesia, label semacam ini tidak berhenti di ruang asesmen, tetapi bisa memengaruhi perlakuan guru, ekspektasi sekolah, bahkan kebijakan lanjutan. Anak yang sejak awal diberi cap “rendah†berpotensi mengalami kekerasan simbolik yang berkepanjangan dalam sistem pendidikan.
Kembalikan MBG pada Hak Anak Dan Orangtua
Evaluasi Kemendikdasmen juga mencatat dampak positif lain, seperti peningkatan kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) sebesar 3,79 persen di sekolah pelaksana MBG. Ini menunjukkan bahwa program gizi mampu mendorong habituasi perilaku hidup sehat secara kolektif—sebuah capaian penting yang sering luput dari perdebatan soal angka.
Kepala SD Negeri 24 Rufei di Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, menyaksikan langsung perubahan di kelasnya. Anak-anak lebih fokus, lebih aktif, dan lebih ceria. Kesaksian semacam ini menegaskan bahwa dampak pendidikan tidak selalu bisa direduksi menjadi skor tes.
Kritik terhadap tes IQ bukan penolakan terhadap evaluasi, melainkan ajakan untuk menggunakan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual. Negara perlu memastikan bahwa MBG tetap diposisikan sebagai hak, bukan alat seleksi; sebagai fondasi, bukan alat ukur prestasi.
Pada akhirnya, memberi makan anak adalah tindakan moral dan konstitusional. Mengujinya dengan angka kecerdasan berisiko menggeser makna itu. Jika negara ingin membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, maka kebijakan evaluasi harus berpihak pada tumbuh kembang anak secara utuh—bukan sekadar pada hasil tes yang mudah dihitung, tetapi sulit dimanusiakan.
Tim Schoolmedia






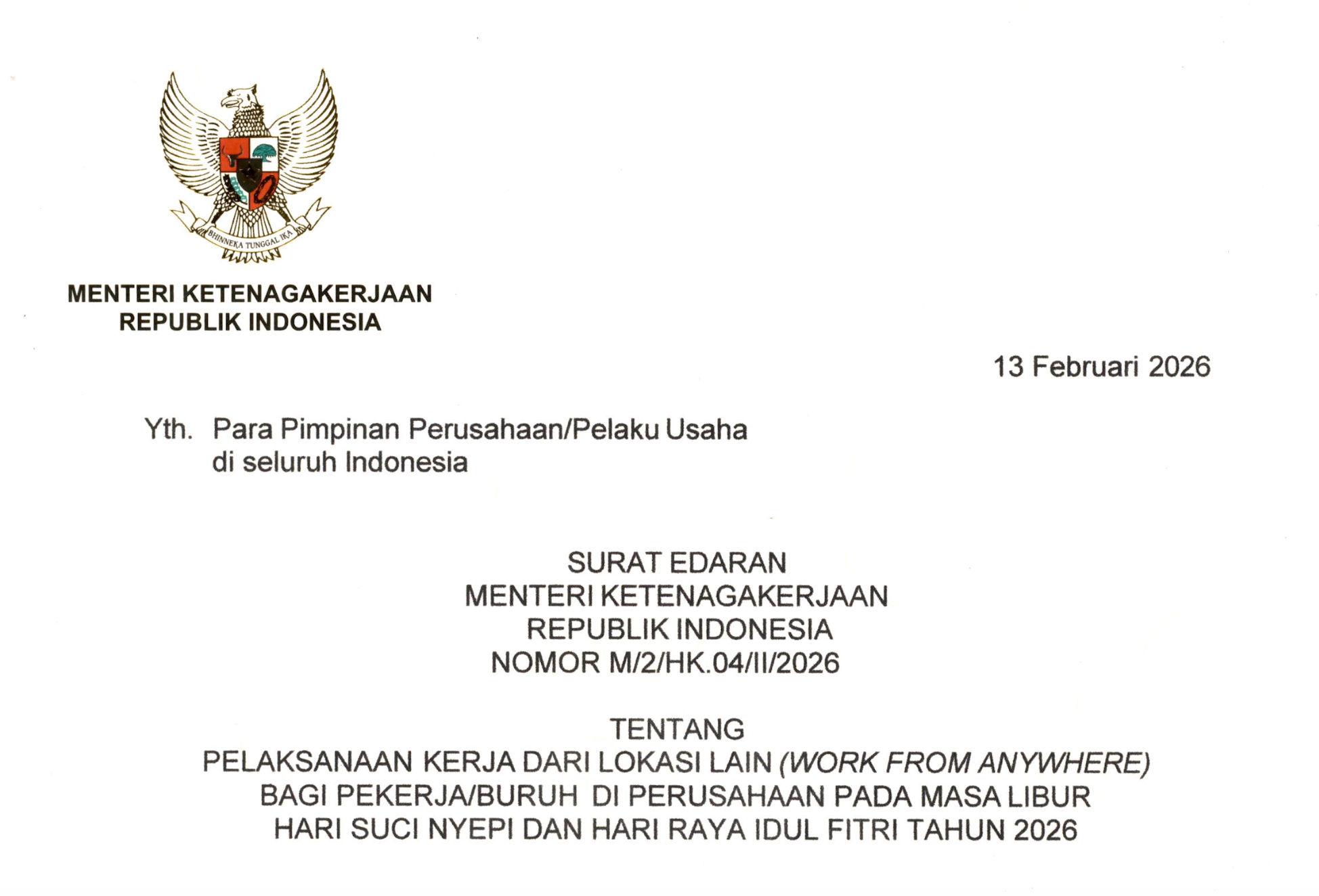
Tinggalkan Komentar